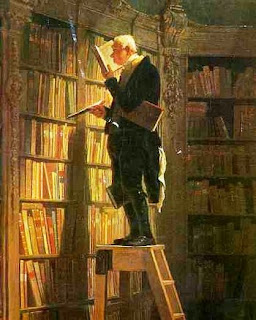
“Setiap bulan sedikitnya saya membeli 300 buku,” demikian budayawan Raufik Rahzen (45) bertutur di sebuah perhelatan kutu buku bertajuk “Temu Blogger Buku” di Kafe Matahari/Domus, Jakarta, Sabtu (17/5) pekan lalu. “Kadang-kadang bisa juga sampai 600 buku,” tambahnya lagi seolah belum puas mengejutkan para hadirin yang berjumlah seratusan orang itu dengan angka 300-nya, termasuk saya yang kebetulan bertindak sebagai moderator.
Hah? Enam ratus sebulan? Oh..oh…tetamu di ruangan bernuansa remang-remang siang itu yang berani-beraninya mengaku kutu buku, kudu menjura seratus kali kepada pria berkaca mata itu, lagi-lagi, termasuk saya yang telah dengan sombongnya gembar-gembor ihwal penyakit belanja buku; padahal cuma mampu beli buku lima biji sebulan. Buat saya, dan mungkin mayoritas rakyat Indonesia, buku masih menjadi barang mewah yang mahal.
Namun, masih menurut Ketua Yayasan Blora ini, rendahnya minat baca masyarakat kita tidak terkait dengan harga buku yang mahal. Sebab, jika orang sudah suka membaca, ia akan mencari berbagai upaya untuk mendapatkan buku-buku yang ingin dibacanya. Pengagum berat Pramoedya Ananta Toer ini mencontohkan pengalamannya sewaktu masih di kampungnya di Sumbawa dahulu. Ia rela berjalan kaki menempuh jarak sepanjang 35 km demi bisa membaca buku. Sekali lagi, kami dibuat melongo dan akhirnya mesti ikhlas mengakui, bahwa beliau memang pecandu buku sejati.
Buku, semua kita tahu, lewat huruf-huruf di pagina-paginanya telah membukakan jendela bagi mereka yang mengakrabinya. Dan sejarah negeri ini telah mencatat tentang para founding fathers-nya yang kutu buku.
Tengoklah seabad lalu, ketika para pemuda pemberani di sebuah negeri jajahan bernama Hindia Belanda, ramai-ramai berkonggres, membincang nasib tanah air mereka yang merana di bawah kangkangan Belanda. Dimotori oleh seorang dokter lulusan STOVIA–Sekolah kedokteran zaman itu–Wahidin, terbentuklah organisasi pemuda pertama yang diberi nama Budi Utomo. Keanggotaan awalnya terdiri dari para mahasiswa STOVIA itu. Kemudian pada 20 Mei 1908, bertempat di Yogyakarta, Budi Utomo menggelar konggres pemuda pertama. Kelak, hari itu dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Republik ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Dua puluh tahun berikutnya, jejak mereka diikuti oleh para penerus dengan mengumandangkan ikrar kebangsaan, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, di Batavia. Tepatnya di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond, Lapangan Banteng (28 Oktober 1928). Tokoh-tokoh pemuda yang hadir di antaranya Muhammad Yamin dan Amir Sjarifudin. Sementara itu, lewat caranya sendiri Soekarno, Hatta, dan Sjahrir melakukan perlawanan dengan mendirikan partai politik.
Tengoklah biografi para pemuda pemberani itu: Wahidin, Soekarno, Hatta, Yamin, Sjahrir, dan kawan-kawan. Mereka semua kutu buku. Kesadaran dan pencerahan yang mereka alami di antaranya mereka peroleh lewat bacaan-bacaan : literatur, koran, dan majalah. Mereka para pembaca yang rakus, melahap buku apa saja seperti makhluk dari golongan omnivora. Buku-buku telah membangkitan keberanian mereka untuk berontak, melawani kezaliman pemerintah Belanda. Buku-buku pula yang telah mengobar-ngobarkan semangat mereka untuk merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
Yang lebih membanggakan lagi, mereka tak hanya berhenti pada membaca. Mereka juga menulis; melakukan perlawanan lewat tulisan-tulisan di media massa yang terbit kala itu dan membuat gerah para meneer penguasa. Satu per satu anak-anak “nakal” itu pun ditertibkan dengan jalan dibui atau diasingkan ke sebuah nusa yang jauh dari ibu kota.
Namun, ternyata penjara dan pengasingan tak lantas menyurutkan semangat perlawanan anak-anak muda ini. Dari tempat pembuangan itu, dengan ditemani buku-buku, mereka terus menulis dan menyebarluaskan gagasan kemerdekaan ke dunia luar. Sebab, mereka pasti sepakat, bahwa menulis adalah juga sebuah tindakan revolusioner.
Jika tak segan menoleh lebih ke belakang lagi, kita akan bertemu Kartini, seorang raden ayu berpendidikan sekolah rendah Belanda yang telah mencengangkan dunia lewat surat-suratnya. Surat-surat itu tak semata berisi curahan hati si gadis Jawa, tetapi juga memuat pikiran-pikiran dan keprihatinan Kartini kepada rakyat kecil yang menderita di bawah tindasan para penguasa (Belanda dan priyayi Jawa). Dari mana gadis lugu yang sejak umur 12 tahun dipingit itu memiliki kesadaran sedemikian rupa? Dari mana lagi kalau bukan dari buku-buku yang diperolehnya melalui sahabat-sahabat korespondensinya.
Mendadak saya iseng membayangkan, andaikata waktu itu teknologi internet dan blog sudah ada, tentu Soekarno, Hatta, Yamin, Sjahrir, Kartini, Tan Malaka, dan gerombolan “anak nakal” lainnya, pasti akan ramai-ramai nge-blog. Dan tentu Indonesia tak perlu menunggu selama 350 tahun plus 3,5 tahun untuk merdeka.
Dan pekan lalu, agaknya Taufik Rahzen beserta segenap penyelenggara acara, ingin menyebar-nyebarkan virus dan mengajak sebanyak-banyak orang menjadi kutu buku lewat kebiasaan membaca dan menulis (blog). Mungkin apa yang dilakukan oleh Taufik Rahzen dan gerombolannya hanyalah ibarat setetes air di tengah samudera, namun semoga bisa menyegarkan.
Saya akhiri tulisan sok tahu ini dengan mengutip sajak “Di Toko Buku” milik penyair Hasan Aspahani yang juga teramat mencintai buku:
Diam-diam aku sedang mempersiapkan
Sebuah kematian yang paling sempurna:
Dikuburkan di dalam buku. Engkau tahu?
Buku akan hidup abadi. Tak mati-mati!
Barangkali saja, kelak dalam perjalananku
Dari halaman-halamanmu, duhai Bukuku,
Duhai Kuburku, duhai Kekasih Abadiku,
bisa kutemukan pertanyaan teka-tekimu,
bisa kudengar apa saja yang dikata Waktu.***
Hah? Enam ratus sebulan? Oh..oh…tetamu di ruangan bernuansa remang-remang siang itu yang berani-beraninya mengaku kutu buku, kudu menjura seratus kali kepada pria berkaca mata itu, lagi-lagi, termasuk saya yang telah dengan sombongnya gembar-gembor ihwal penyakit belanja buku; padahal cuma mampu beli buku lima biji sebulan. Buat saya, dan mungkin mayoritas rakyat Indonesia, buku masih menjadi barang mewah yang mahal.
Namun, masih menurut Ketua Yayasan Blora ini, rendahnya minat baca masyarakat kita tidak terkait dengan harga buku yang mahal. Sebab, jika orang sudah suka membaca, ia akan mencari berbagai upaya untuk mendapatkan buku-buku yang ingin dibacanya. Pengagum berat Pramoedya Ananta Toer ini mencontohkan pengalamannya sewaktu masih di kampungnya di Sumbawa dahulu. Ia rela berjalan kaki menempuh jarak sepanjang 35 km demi bisa membaca buku. Sekali lagi, kami dibuat melongo dan akhirnya mesti ikhlas mengakui, bahwa beliau memang pecandu buku sejati.
Buku, semua kita tahu, lewat huruf-huruf di pagina-paginanya telah membukakan jendela bagi mereka yang mengakrabinya. Dan sejarah negeri ini telah mencatat tentang para founding fathers-nya yang kutu buku.
Tengoklah seabad lalu, ketika para pemuda pemberani di sebuah negeri jajahan bernama Hindia Belanda, ramai-ramai berkonggres, membincang nasib tanah air mereka yang merana di bawah kangkangan Belanda. Dimotori oleh seorang dokter lulusan STOVIA–Sekolah kedokteran zaman itu–Wahidin, terbentuklah organisasi pemuda pertama yang diberi nama Budi Utomo. Keanggotaan awalnya terdiri dari para mahasiswa STOVIA itu. Kemudian pada 20 Mei 1908, bertempat di Yogyakarta, Budi Utomo menggelar konggres pemuda pertama. Kelak, hari itu dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Republik ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Dua puluh tahun berikutnya, jejak mereka diikuti oleh para penerus dengan mengumandangkan ikrar kebangsaan, yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, di Batavia. Tepatnya di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond, Lapangan Banteng (28 Oktober 1928). Tokoh-tokoh pemuda yang hadir di antaranya Muhammad Yamin dan Amir Sjarifudin. Sementara itu, lewat caranya sendiri Soekarno, Hatta, dan Sjahrir melakukan perlawanan dengan mendirikan partai politik.
Tengoklah biografi para pemuda pemberani itu: Wahidin, Soekarno, Hatta, Yamin, Sjahrir, dan kawan-kawan. Mereka semua kutu buku. Kesadaran dan pencerahan yang mereka alami di antaranya mereka peroleh lewat bacaan-bacaan : literatur, koran, dan majalah. Mereka para pembaca yang rakus, melahap buku apa saja seperti makhluk dari golongan omnivora. Buku-buku telah membangkitan keberanian mereka untuk berontak, melawani kezaliman pemerintah Belanda. Buku-buku pula yang telah mengobar-ngobarkan semangat mereka untuk merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
Yang lebih membanggakan lagi, mereka tak hanya berhenti pada membaca. Mereka juga menulis; melakukan perlawanan lewat tulisan-tulisan di media massa yang terbit kala itu dan membuat gerah para meneer penguasa. Satu per satu anak-anak “nakal” itu pun ditertibkan dengan jalan dibui atau diasingkan ke sebuah nusa yang jauh dari ibu kota.
Namun, ternyata penjara dan pengasingan tak lantas menyurutkan semangat perlawanan anak-anak muda ini. Dari tempat pembuangan itu, dengan ditemani buku-buku, mereka terus menulis dan menyebarluaskan gagasan kemerdekaan ke dunia luar. Sebab, mereka pasti sepakat, bahwa menulis adalah juga sebuah tindakan revolusioner.
Jika tak segan menoleh lebih ke belakang lagi, kita akan bertemu Kartini, seorang raden ayu berpendidikan sekolah rendah Belanda yang telah mencengangkan dunia lewat surat-suratnya. Surat-surat itu tak semata berisi curahan hati si gadis Jawa, tetapi juga memuat pikiran-pikiran dan keprihatinan Kartini kepada rakyat kecil yang menderita di bawah tindasan para penguasa (Belanda dan priyayi Jawa). Dari mana gadis lugu yang sejak umur 12 tahun dipingit itu memiliki kesadaran sedemikian rupa? Dari mana lagi kalau bukan dari buku-buku yang diperolehnya melalui sahabat-sahabat korespondensinya.
Mendadak saya iseng membayangkan, andaikata waktu itu teknologi internet dan blog sudah ada, tentu Soekarno, Hatta, Yamin, Sjahrir, Kartini, Tan Malaka, dan gerombolan “anak nakal” lainnya, pasti akan ramai-ramai nge-blog. Dan tentu Indonesia tak perlu menunggu selama 350 tahun plus 3,5 tahun untuk merdeka.
Dan pekan lalu, agaknya Taufik Rahzen beserta segenap penyelenggara acara, ingin menyebar-nyebarkan virus dan mengajak sebanyak-banyak orang menjadi kutu buku lewat kebiasaan membaca dan menulis (blog). Mungkin apa yang dilakukan oleh Taufik Rahzen dan gerombolannya hanyalah ibarat setetes air di tengah samudera, namun semoga bisa menyegarkan.
Saya akhiri tulisan sok tahu ini dengan mengutip sajak “Di Toko Buku” milik penyair Hasan Aspahani yang juga teramat mencintai buku:
Diam-diam aku sedang mempersiapkan
Sebuah kematian yang paling sempurna:
Dikuburkan di dalam buku. Engkau tahu?
Buku akan hidup abadi. Tak mati-mati!
Barangkali saja, kelak dalam perjalananku
Dari halaman-halamanmu, duhai Bukuku,
Duhai Kuburku, duhai Kekasih Abadiku,
bisa kutemukan pertanyaan teka-tekimu,
bisa kudengar apa saja yang dikata Waktu.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar